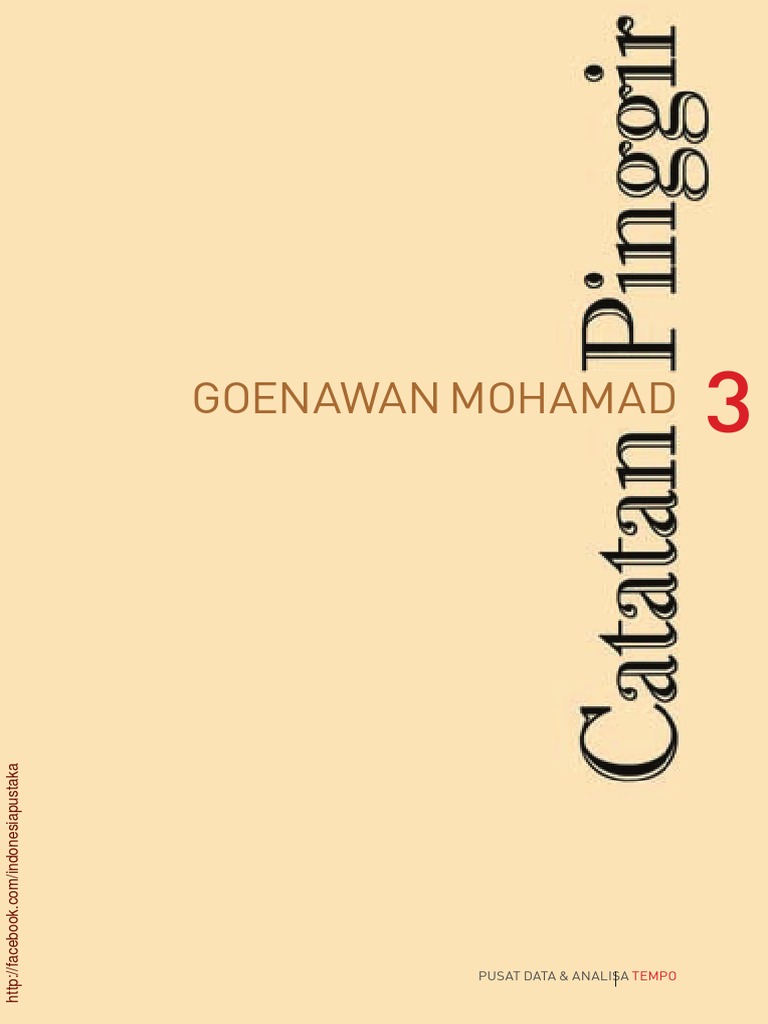Oleh Ignas Kleden
DALAM kalangan ahli-ahli ilmu sosial Clifford Geertz dikenal sekurang-kurangnya dalam dua kedudukan. Pertama, dia adalah seorang ahli Indonesia – seorang Indonesaianis, menurut istilah akademiknya – yang karya-karyanya menjadi bacaan wajib bagi peneliti atau calon peneliti Indonesia. Dalam kedudukan itu dia dapatlah dibandingkan dengan George McT. Kahin, Robert R. Jay, Ben Anderson, Dwight Y. King, James L. Peacock, Herbert Feith, James Siegel, atau Daniel Lev, untuk menyabutkan beberapa nama yang paling dikenal oleh masyarakat intelektual Indonesia. Kedua, dia juga dikenal sebagai seorang ahli antropologi yang memberi perhatian besar kepada pembentukan teori, baik mengenai hal-hal yang menyangkut kebudayaan maupun mengenai kehidupan masyarakat.
Dalam studi kebudayaan, sumbangan C. Geertz terlihat dalam konsep-konsep yang diajukannya tentang berbagai soal dalam kebudayaan: agama, ideologi, negara teater, common sense, simbol, integrasi, pandangan dunia, etos dan makna. Dalam kedudukan sebagai ahli kebudayaan nama C. Geertz dapat disejajarkan dengan tokoh-tokoh seperti Raymond Firth, Victor W. Turner, Mary Douglas, Susanne K. Langer atau pun Marvin Harris. Demikian pula dalam studi-studi kemasyarakatan sumbangan C. Geertz tak dapat diabaikan. Konsep-konsep seperti involusi, aliran, ekonomi bazar, atau hollow town/solid town, adalah sumbangan penting dalam studi-studi sosial yang membuatnya tidak saja dikenal dalam kalangan ahli antropologi tetapi dalam kalangan yang lebih luas. Involusi misalnya adalah sebuah masalah yang untuk waktu yang cukup lama menjadi bahan perdebatan di antara para ahli pertanian, seperti konsepnya tentang aliran membuatnya diperhatikan oleh ahli-ahli ilmu politik, konsepnya tentang perkotaan menjadi rujukan dalam berbagai studi sosiologi perkotaa, sedangkan konsepnya tentang ekonomi bazar menjadi bahan perdebatan dalam antropologi dan sosiologi ekonomi. Di sini nama dan pendapatnya dapatlah disejajarkan dengan James C. Scott atau Samuel L. Popkin, dan Benyamin White dalam studi tentang pertanian, dengan Karl Polanyi, Mark Granovetter, atau pasangan Paul Alexander dan Jennifer Alexander dalam sosiologi dan antropolgi ekonomi, dengan W.F. Werthein dalam studi tentang pengelompokan politik di Indonesia tahun 1950-an, dan juga dengan Hans Dieter Evers atau Terence Gary McGee dalam studi-studi antropologi perkotaan.
Sudah tentu kedua kedudukan itu tak terpisahkan, karena berbagai konsep kebudayaan dan konsep tentang struktur dan perubahan sosial yang dihasilkan Geertz berasal terutama dari penelitainnya di Indonesia, khususnya di Jawa dan Bali pada tahun 50-an. Dengan demikian kedudukannya sebagai seorang teoretikus berkembang bersamaan dengan kariernya sebagai seorang peneliti yang tangguh dan subur tentang kebudayaan dan masyarakat Indonesia.
Geertz memulai karier ilmiahnya sebagai peneliti Indonesia, khususnya peneliti Jawa dan Bali. Dari masa ini dia telah menghasilkan berbagai karya yang kini dikenal luas baik dalam komunitas ilmuwan sosial, mau pun dalam kalangan cendekiawan Indonesia. Buku-buku tersebut adalah The Religion of Java(1), yaitu disertasinya, yang merupakan etnografi yang amat lengkap tentang masyarakat Jawa, dan menjadi terkenal karena di sini diperkenalkan konsep aliran, sebagai sebuah konsep kebudayaan dan sebagai sebuah konsep tentang pengelompokan politik di Indonesia pada tahun 1950-an; Peddlers and Princes(2), sebuah studi antropologi ekonomi di mana penulisnya mengemukakan konsep ekonomi bazar dalam perdagangan Indonesia pada tahun 1950-an; The Social History of an Indonesia Town(3), sebuah studi perkotaan tempat Geertz memperkenalkan konsep hollow town/solid town; Agricultural Involution(4), sebuah studi tentang pertanian di Jawa, di mana Geertz melansir konsep tentang involusi pertanian sebagai sebuah kemungkinan lain dari dari evolusi; Islam Observed(5), sebuah studi perbandingan tentang perkembangan Islam di Maroko dan Indonesia, tempat Geertz mengembangkan konsepnya tentang the force of religion dan the scope of religion; dan juga Negara: The Theatre State in Nineteenth Century Bali (6), sebuah studi tentang politik klasik di Bali pada abad ke-19, di mana dia menguraikan konsep-konsep seperti estate dan stateliness yang demikian penting dalam politik klasik, tetapi yang menurut pendapatnya amat diabaikan oleh ilmu politik moderen yang hanya memperhatikan konsep statecraft.
Pembaca dan khususnya mahasiswa di Indonesia sekarang amat beruntung mempunyai akses yang luas terhadap penelitian-penelitian tersebut, karena selain buku Negara, maka semua buku lainnya, setahu penulis, sudah diterjemahkan dengan cukup baik ke dalam bahasa Indonesia.
Tidak perlu dijelaskan kiranya bahwa dalam penelitian tersebut, Geertz tidak bisa menghindar dan harus menggunakan berbagai teori, konsep dan metode, baik dalam ilmu antropologi budaya dan antropologi sosial, mau pun peralatan konseptual dan metedologis yang tersedia dalam ilmu-ilmu sosial umumnya. Tahapan ini merupakan tahapan pertama dalam karier ilmiah C. Geertz yang untuk mudahnya kita namakan tahapan studi empiris. Di sini berbagai peralatan konseptual dan metedologis itu diterapkan, dimodifikasi dan kemudian diperbaharui, atau bahkan dibantah dalam suatu penelitian empiris di lapangan. Tentu saja penelitian dapat sekaligus menjadi tempat dan kesempatan sebuah konsep atau bahkab teori dihasilkan. Sebagai contoh studi Geertz tentang sejarah pertanian di Jawa khususnya sejak Tanam Paksa (1840-1870), akhirnya menelorkan teorinya tentang involusi pertanian yang banyak diperdebatkan itu. Namun teori ini lebih merupakan penerapan dan modifikasi teori involusi yang dikembangkan sebelumnya oleh Goldenweiser dalam bidang kesenian dan estetika (7). Jadi pembaharuan yang dilakukan Geertz adalah memindahkan sebuah teori estetika dan menerapkannya dalam studi agronomi.
Tahapan kedua dalam pemikiran Cilfford Geertz ditandai oleh studi-studinya yang bersifat teoritis, yang cukup berbeda dari studi-studi empirisnya. Kalau dalam penelitian empiris, sebuah konsep, teori dan metode diterapkan untuk menguraikan dan menjelaskan suatu gejala kemasyarakatan atau suatu gejala kebudayaan, maka dalam studi teoritis, teori, konsep dan metode itu sendiri yang menjadi sasaran penelitian dan obyek penyelidikan. Yang diteliti di sana bukan lagi suatu gejala kebudayaan seperti pandangan hidup orang Jawa atau gejala kemasyarakatan seperti struktur sosial di Bali, tetapi pemikiran, pengandaian, kecenderungan, dan bahkan prasangka-prasangka yang menjadi unsur konstitutif dalam pembentukan suatu teori atau metode, entah unsur-unsur itu dipergunakan dengan sengaja dan sadar, mau pun kalau unsur-unsur tersebut menyelinap masuk tanpa disadari atau diawasi. Untuk mengatakannya secara gampang, studi-studi teoritis ini menyelidiki rancang bangun atau arsitektur sebuah teori, konsep atau metode, dan dapat dinamakan tahapan studi teoritis.
Untuk memberi sebuah contoh saja, dalam studinya tentang konsep kebudayaan, Geertz menunjukkan dengan cukup konsisten bahwa konsep itu selalu terdiri dari bahagian utama, yaitu kebudayaan sebagai sistem pengetahuan dan sistem makna, dan kebudayaan sebagai sistem nilai. Bahagian pertama dinamakannya juga aspek kognitif kebudayaan, sedangkan bagian lainnya dinamakannya aspek evaluatif kebudayaan. Aspek kognitif ini sebagai sebuah bentuk representasi dinamakannya model of atau ‘model tentang’, sedangkan aspek evaluatif sebagai sebuah bentuk representasi dinamakannya model for atau ‘model untuk’. Model yang pertama (model of) merepresentasikan kenyataan yang ada (atau sudah ada) seperti halnya sebuah peta pulau Sumatra merupakan model tentang pulau Sumatra. Dalam model ini sebuah struktur simbolis (misalnya peta) disesuaikan dengan sebuah struktur non-simbolis, sebutlah, suatu struktur fisik (misalnya pulau Sumatra).
Sebaliknya sistem nilai atau sistem evaluatif berupa model for tidak merepresentasikan suatu kenyataan yang sudah ada melainkan suatu kenyataan yang masih harus dibentuk atau diwujudkan. Dalam arti itu sebuah maket untuk perumahan atau kondominium adalah ‘model untuk’ perumahan atau kondominium yang masih harus dibangun. Di sini suatu struktur non-simbolis, atau struktur fisik (misalnya kompleks perumahan atau kondominium) harus disesuaikan dengan struktur simbolis berupa maket atau bahkan ide yang ada di kepala si arsitek.
Persoalan teoritis yang muncul di sini adalah faktor atau instansi mana dalam kebudayaan yang berfungsi menghubungkan sistem pengetahuan dan sistem nilai? Atau, apa yang memungkinkan bahwa suatu pengetahuan diterjemahkan menjadi nilai, atau sebaliknya, seperangkat nilai dapat diterjemahkan menjadi pengetahuan? Jawaban Geertz: sistem simbol. Dengan demikian kalau kita dapat menyederhanakan pandangan Geertz tentang konsep kebudayaan, maka konsep ini akan terdiri dari tiga bahagian utama yaitu sistem pengetahuan atau sistem kognitif, sistem nilai atau sistem evaluatif, dan sistem simbol yang memungkinkan interpretasi. Ada pun titik pertemuan antara pengetahuan dan nilai yang dimungkinkan oleh simbol inilah yang dinamakan makna (system of meaning). Melalui makna sebagai suatu instansi pengantara maka sebuah simbol dapat menerjemahkan seperangkat nilai menjadi suatu sistem pengetahuan.
Sebuah contoh yang amat ilustratif dapat diambil dari uraian Geertz mengenai dunia perwayamgan. Dalam wayang nampaknya ada pengetahuan yang hendak di lestarikan yaitu bahwa segala sesuatu – juga kebaikan atau sifat-sifat baik pada manusia – taka boleh berlebih dari ukuran. Semacam virtus in medio (kebajikan selalu ada di tengah-tengah) dalam kebudayaan Romawi klasik. Anggapan yang berlaku di sini adalah bahwa setiap sifat baik, kalau menjadi berelebihan, akan menimbulkan keadaan sebaliknya yang tidak baik lagi. Yudhistira misalnya adalah simbol kemurahan hati dan simbol rasa peka terhadap penderitaan orang lain. Namun demikian, siafat-siafat inilah yang membuatnya tak mampu memerintah negeri. Dia terlalu mudah jatuh kasihan dan tidak sanggup bersikap tega. Kemurahan hati akhirnya membuatnya miskin dan rasa belas-kasihannya membuatnya lemah dalam menjalankan dan mempertahankan kekuasaan. Bima sebaliknya, adalah simbol keteguhan hati, watak yang kuat dan sikap tegas. Namun demikian, siafat-siafat inilah yang membuatmya sering terlibat konflik dan mengalami bentrokan dengan pihak lain. Arjuna adalah simbol keadilan dan sikap jujur, tetapi juga sekaligus menjadi simbol intoleransi terhadap orang-orang yang lemah moralnya atau mereka yang kebetulan sedang jatuh ke dalam penyelewengan dan kekhilafan.
Melalui simbol-simbol ini pengetahuan tentang ambivalensi sifat manusia diterjemahkan menjadi makna, yaitu bahwa setiap tokoh Pandawa tidak bisa hidup dan bertindak sendiri-sendiri. Mereka hanya bisa efektif kalau berada bersama dan bekerja bersama. Dalam kerja sama tersebut kelemahan sifat tokoh yang satu dapat diimbangi oleh keunggulan sifat tokoh yang lainnya. Tiap tokoh Pandawa secara perorangan akan terbentur pada kesulitan yang timbul bukan dari kecenderungan kepada hal yang jahat, tetapi justru dari sifat-sifat baik yang dikembangkan secara tak terukur dan tak terawasi. Karena itu mereka hanya efektif kalau tampil dan berkiprah sebagai Pandawa Lima.
Di sini terlihat jelas semua unsur yang membentuk konsep kebudayaan. Ada pengetahuan yang disampaikan tentang sifat-sifat manusia dan ambivalensinya. Ada simbol untuk sifat-sifat tersebut yaitu para tokoh Pandawa Lima. Simbolik tokoh-tokh ini pun cukup jelas: tiap mereka merepresentasikan kebaikan tetapi sekaligus juga menyembunyikan kelemahan yang tersembunyi di balik sifat-sifat baik tersebut. Dalam pandangan Raymond Firth simbol dirumuskan sebagai kemampuan ganda untuk menyatakan dan menyembunyikan, atau malahan kemampuan untuk menyatakan sesuatu dengan menyembunyikan, dan menyembunyikan sesuatu dengan menyatakannya. Simbol sebagai gabungan dari concealment dan revelation (8) nampak jelas dari sifat-sifat baik yang direpresentasikan dalam keutamaan dan kebajikan tokoh-tokoh Pandawa dan kelemahan yang tersembunyi di baliknya. Selanjutnya, cukup jelas juga makna yang hendak ditekankan, yaitu bahwa kebersamaan akan lebih menolong dan lebih efektif dari otonomi individual setiap orang, sedangkan nilai yang dilestarikan adalah keseimbangan dalam segala sesuatu dan harmoni.
Studi-studi teoritis Geertz ini kemudian dikumpulkan dan diterbitkan dalam dua jilid, masing-masingnya berjudul The Interpretation of Culture dan Local Knowledge (10). Buku yang tersebut pertama berisikan studi-studi teoritis sebagaimana sudah diuraikan di atas. Sedangkan buku kedua buat sebahagiannya masih meneruskan tema utama buku pertama yaitu pembahasan tentang konsep-konsep kebudayaan, sementara buat sebahagian lainnya dia menyiapkan ke jalan kepada tahapan ketiga dalam perkembangan pemikiran Geertz.
Buku yang sedang anda hadapi ini, yang dalam edisi asli bahasa Imggris berjudul After the Fact (11), adalah karya yang menurut hemat saya patut dibaca dalam hubungan dengan buku lain yang sudah terbit sebelumnya yang berjudul Works and Lives (12) dan bahkan tak dapat dilepaskan dari beberapa bab dalam Local Knowledge. Kedua jilid ini (dengan dukungan dari Local Knowledge) menandai tahapan ketiga dalam perkembangan pemikiran Geertz.
Sebagaimana sudah disinggung di atas, dalam tahapan pertama Geertz melakukan studi-studi penelitian empiris dengan mengamati, mendalami dan mengulas berbagai kenyataan dalam kebudayaan dan masyarakat Indonesai. Cukup banyak hal yang ditelitinya dalam tahapan ini: pola pertanian Jawa, pola perdagangan di Jawa dan Bali tahun 1950-an, pengelompokan politik di Indonesia pada masa yang sama, perkemabangan dan struktur kota hingga ke sifat politik klasik di Bali dan perkembangan Islam di Jawa. Dalam tahapan studi empiris ini dia menggunakan dan menerapkan berbagai teori, konsep dan metode antropologi dan ilmu sosial lainnya, tanpa terlalu banyak mempersoalkan susunan dan kontruksi teori, konsep dan metode yang digunakan.
Sebaliknya, dalam tahapan kedua, yang di sini dinamakan tahapan studi teoritis, maka teori, konsep dan metode tersebut tidak lagi menjadi sekedar sarana dan peralatan dalam melakukan penelitian, tetapi justru menjadi titik pusat perhatian dan bahan pengkajian. Di sini Geertz coba memeriksa apa yang dinamakan kebudayaan, simbol, pandangan dunia, etos, ideologi, kesenian. Bahkan diselidiki juga konsep manusia yang menjadi landasan terakhir ilmu antropologi. Demikian pun sejauh menyangkut metode dia menguraikan secara mendalam apa yang dinamakan interpretasi, semantik, hermeneutik dan bahkan semiotik. Dengan demikian studi-studi toeritis ini dapat juga dinamakan studi-studi metodologis.
Dalam tahapan ketiga, Geertz mencoba mempertanyakan bukan saja teori dan metode ilmu antropologi, tetapi – lebih dari itu – dia mempertanyakan dan mempersoalkan kedudukan, fungsi dan peran ilmu antropologi itu sendiri. Dalam Works in Lives dipertanyakan kedudukan ilmu antropologi sebagai sebuah disiplin ilmiah dalam kaitan dengan latar belakang kelahiran ilmu pengetahuan ini, kemudian dipersoalkam teks etnografi dalam perbandingan dengan teks-teks lainnya khususnya teks kesusastraan, dan dipersoalkan juga apakah ilmu antropologi masih mempunyai masa depan kalau tetap berpegang pada tradisinya semula. Persoalan lain tentu saja, apakah dan bagaimana caranya ilmu antropologi memperbarui tradisi ilmiahnya sehingga dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan baru. Sebagaimana sudah disinggung di atas, sebagian dari pertanyaan-pertanyaan ini sudah diajukannya dalam Local Knowledge.
Ini berarti, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada tahapan ketiga ini tidak saja bersifat teoritis dan metodologis tetapi menjadi pertanyaan epistemologis, sehingga masa ini dapat dinamakan tahapan studi epistemologis. Perlu dikatakan bahwa istilah epistemologi di sini dipergunakan dalam dua artinya. Pertama, dalam arti tradisional, berupa penyelidikan tentang bangunan logis sebuah teori. Kedua, dalam arti yang lebih baru yang diperkenalkan dalam kalangan postmodernis, yaitu bagaimana sebuah proses genesis sebuah cabang ilmu pengetahuan dipengaruhi oleh konteks historis di mana dia diproduksikan dan direproduksikan.
Secara konkret Geertz mempertanyakan bagaimana ilmu antropologi yang lahir pada abad ke-19 dan perkembangannya banyak didorong oleh kepetingan imperialisme dan kolonialisme Barat harus berpikir ulang tentang peran dan fungsinya, tatkala kedua kekuatan sejarah itu telah menyusut secara drastis semenjak Perang Dunia II. Demikian pun, antropolgi yang tadinya merupakan ilmu yang membawa pengetahuan tentang negeri asing yang jauh, terbelakang, ‘primitif’ dan eksotis ke negeri-negeri yang lebih maju di belahan bumi sebelah Utara, harus berhadapan dengan kenyataan bahwa semakin banyak ahli antropologi kini hidup, bekerja dan meneliti di negerinya sendiri. Demikian pun kalau kita membaca sebuah teks etnografi atau bahkan kalau kita sendiri harus menuliskannya, apakah teks kita ini harus diperlakukan secara amat berbeda dengan catatan harian, laporan perjalanan, atau sebuah prosa sastra yang indah? Bukankah Levi-Strauss menulis dengan gaya travelog dan selalu berusaha dengan sadar mendekatkan dirinya pada tradisi sastra Baudelire, Mallarme atau Rimbaud? Bukankah Malinowski menulis A Diary in The Strict Sense of The Term?
Kalau Works and Lives adalah hasil perenungan Geertz tentang kedudukan ilmu antropologi dengan merujuk kepada apa yang telah dilakukan oleh empat antropolog besar yang karya-karyanya kini telah menjadi klasik (yaitu Levi-Strauss, Evans-Pritchard, Malinowski dan Ruth Benedict), maka After the Fact adalah hasil perenungannya tentang kedudukan ilmu pengetahuan ini dengan merujuk kepada apa yang telah dilakukannya dan dialaminya sendiri dalam ilmu antropologi selama empat dasawarsa di dua negeri tempatnya meneliti. Maka subjudul buku ini terbaca bagaikan sebuah pengakuan dalam nostalgia: Two Countries, Four Decades, One Anthropologist.
Tentulah pengantar ini tidak boleh mendahului para pembaca dalam menentukan kesan dan penangkapan kepada isi, susunan, dan gaya buku ini. Setiap orang dapat mengembangkan dialog yang khas dengan karya yang dibacanya. Namun satu hal bisa dikatakan sambil lalu di sini, bahwa setelah empat dasawarsa bekerja dalam cabang ilmu pengetahuan sosial ini, Geertz, dalam retropreksi, seakan memandang ilmu antropologi bukan hanya sebagai suatu disiplin ilmiah tetapi juga sebagai sebuah suratan hidup. Adalah studi antropologi yang telah membawanya mengembara ke dua negeri asing, dan adalah pengalamannya dengan kedua negeri inilah yang kurang lebih memberi bentuk kepada pengertiannya yang khas tentang disiplin tempat dia bekerja, berkiprah, dan memandang dunia.
Buku ini, mungkin dengan cara yang sedikit berlebihan, dapat dinamakan juga sebuah etnografi, tetapi bukan etnografi tentang Pare di Jawa Timur atau tentang Sefrou di Maroko, tetapi sebuah etnografi tentang ilmu antropologi dan tentang pengalaman pengarangnya selama berada dan bekerja di sana. Sebagaimana etnografi adalah cerita dan laporan seorang peneliti tentang pengalamannya berada dalam suatu kebudayaan lain (dengan tema cerita I have been there), maka buku yang sedang atau akan anda baca ini adalah cerita Geertz tentang pengalamannya berada dalam ilmu antropologi selama empat dasawarsa (juga dengan tema cerita I have been there).
After the Fact pada akhirnya adalah sebuah antrpologi tentang ilmu antropologi dan sebuah etnografi tentang etnografi.



———————————————————————-
*Tulisan ini adalah “Pengantar” dalam Buku After the Fact, Dua Negeri, Empat Dasawarsa, Satu Antropolog, Clifford Geertz, LkiS.
Catatan Kaki:
- Clifford Geertz, The Religion of Java, Chicago, University of Chicago Press, 1960.
- Clifford Geertz, Peddlers and Princes: Social Change and Economic Modernization in Two Indonesian Towns, Chicago, University of Chicago Press, 1963.
- Clifford Geertz, The Social History of an Indonesia Town, Chicago, University of Chicago Press, 1965.
- Clifford Geertz, Agricultural Involution: The Process of Ecological Change in Indonesia, Berkley & Los Angeles, University of California Press, 1963.
- Clifford Geertz,Islam Observed: Religious Development in Morocco and Indonesai, Chicago, University of Chicago Press, 1968.
- Clifford Geertz, Negara: The Theatre State in Nineteenth Century Bali, New Jersey, Princeton University Press, 1980.
- Goldenweiser,”Loose Ends of a Theory on the Individual Pattern and Ivolution in Primitve Society”, yang diterbitkan dalam R. Lowie (Ed), Essays in Antropology Presented to A. L. Kroeber, Berkeley University of California Press, 1936.
- Raymond Firth, Symbols: Public and Private, London, George Allen & Unwin Ltd., 1975, p. 15 ff.
- Clifford Geertz, The Interpertation of Cultures Selected Essays, New York, Basic Bookk, 1973.
- . Clifford Geertz, Local Knowledge: Further Essays Interpretive Anthropology, New York, Basic Bookk, 1983.
- . Clifford Geertz, After the Fact: Two Countries, Four Decades, One Antrhopologist, Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press, 1995.
- . Cliiford Geertz, Works and Lives: The Anthropologist as Author, Cambridge, Polity Press, 1989 (1988)