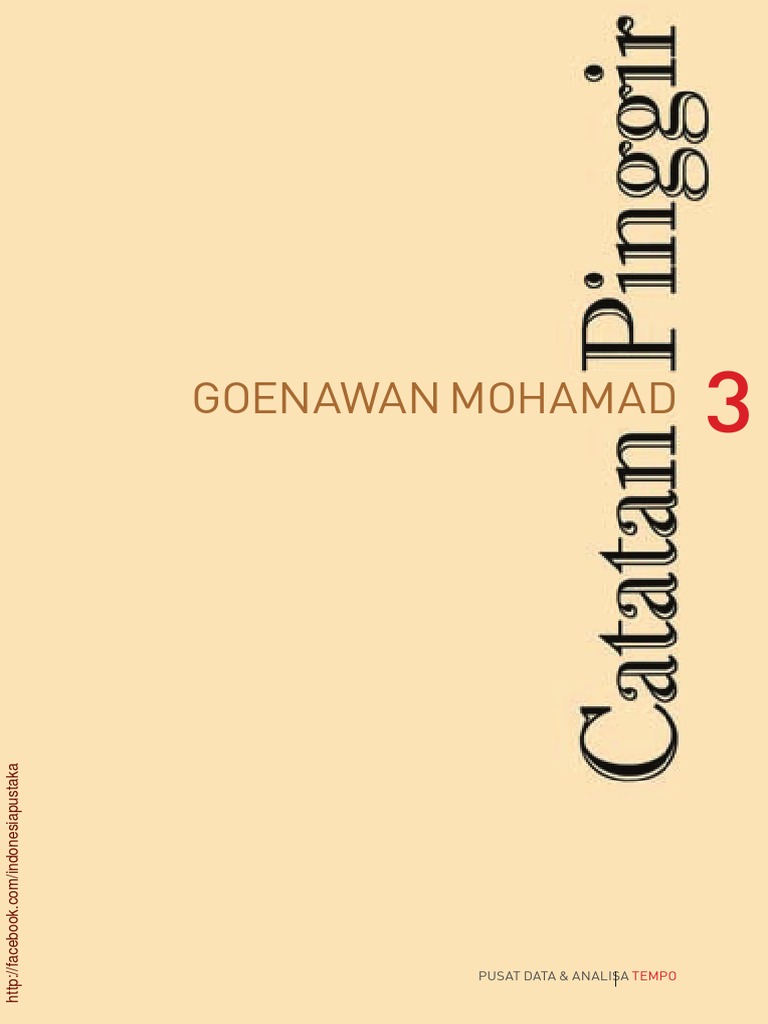Oleh R. William Liddle
”Every writer has an address.” —Isaac Bashevis Singer
SETIAP penulis memiliki ”rumah”. Pendapat ini dikutip dan diterangkan oleh Cynthia Ozick, seorang sastrawan Amerika, dalam sebuah interviu dengan The New York Times baru-baru ini. Juga mengutip Shakespeare bahwa kehidupan moral mempunyai ”a habitation and a name”, bertempat tinggal dan bernama, Ozick menegaskan bahwa seorang penulis mau tidak mau mencerminkan sifat-sifat kebudayaan dan peradaban tempat ia lahir dan dibesarkan.
Lebih dari itu, Ozick menganjurkan supaya pernyataan tersebut dijadikan pcdoman hidup bagi setiap sastrawan. ”If you want to live the life that can best bring you into a sense of being a civilized person, then you have to seize it through your own culture.” Kalau Anda ingin menghayati kehidupan yang akan menyebabkan Anda merasa menjadi orang beradab, Anda harus merebutnya melalui budaya Anda sendiri.
Rumah Isaac Bashevis Singer dan Cynthia Ozick tidak perlu diragukan lagi. Mereka adalah penulis Yahudi yang selalu menciptakan cerita dengan latar belakang, sasaran, dan perhatian yang penuh kepekaan terhadap masyarakat Yahudi, khususnya masyarakat Yahudi di Eropa dan Amerika yang langsung atau tidak langsung mengalami pembinasaan komunitas mereka di kamp tahanan Nazi.
Apakah para penulis Indonesia memiliki rumah, tempat tinggal, dan nama? Mungkin sebagian besar cendekiawan Indonesia akan mengatakan bahwa bangsa Indonesia, berbeda dengan orang Yahudi atau bangsa Barat pada umumnya, belum memiliki kebudayaan (apalagi peradaban!) yang sejati. Dengan kata lain, belum memiliki rumah.
Pandangan umum ini pernah tecermin dalam sebuah perdebatan yang terjadi lebih dari 50 tahun yang lalu, yang kemudian terkenal setelah dibukukan dengan judul Polemik Kebudayaan. Yang diperdebatkan adalah Barat lawan Timur.
Satu pihak, yang diwakili Sutan Takdir Alisjahbana, berpendapat bahwa masyarakat Indonesia harus meninggalkan budaya lama atau tradisional, dan mengadopsi budaya Barat yang dianggap rasional dan ilmiah. Sebelum abad ke-20, kata pihak ini, sebelum tercipta ide negara kebangsaan Indonesia, belum ada budaya Indonesia.
Pihak lain, diwakili oleh Sanusi Pane, melihat budaya nasional Indonesia yang ingin dikembangkan pada masa mendatang sebagai puncak-puncak berbagai budaya tradisional yang luhur, dan oleh karena itu harus diselamatkan dan dilestarikan. Pihak yang kedua ini tidak menolak mentah-mentah pendekatan ilmiah, tetapi merumuskan budaya Indonesia yang diidamkan sebagai perpaduan antara dua unsur: unsur Barat, yang materialistis; dan unsur Timur, yang spiritualistis.
Dalam masyarakat intelektual Indonesia (dan banyak negara berkembang lain di Asia), perdebatan Timur-Barat yang berawal pada zaman penjajahan tersebut bergema terus sampai sekarang. Versi mutakhir perdebatan itu bermacam-macam: ada yang canggih dan ada yang dangkal, ada yang pro Barat dan ada yang pro Timur, dan tentu ada pula yang menawarkan berbagai rumusan baru. Tetapi kesemuanya berkisar pada dua pengertian pokok: bahwa inti persoalannya tercakup dalam peta budaya dengan dua kutub itu; dan bahwa masih belum ada pemecahan persoalan dalam bentuk budaya baru yang dimiliki bersama oleh sebagian besar bangsa Indonesia.
Goenawan Mohamad adalah burung langka dalam sangkar intelektual modern Indonesia. Dia menolak tegas pengkotakan Timur-Barat. Lebih penting lagi, dia jelas menulis sebagai warga sah masyarakat Indonesia yang sudah berkebudayaan nasional. Dengan kata lain, Goenawan, seperti halnya Singer dan Ozick, sudah memiliki rumah.
Dalam sejumlah Catatan Pinggir ini, dikotomi Timur-Barat beberapa kali ditampik Goenawan. Dalam ”Hikayat Abdullah”, dia menyerang orang yang menganggap ide-ide dari Barat sebagai barang yang tidak ”bisa bergabung dengan pegangan yang dibawa dari rumah, dalam suatu proses yang tak saling menyobek.” Di lain pihak, ”polemik” bercerita tentang seorang Jepang dari abad ke-18 yang memperkenalkan ilmu anatomi berdasarkan ”kehidupan yang nyata”, kepada masyarakatnya. Kata Goenawan: ilmu empiris, science, adalah sesuatu yang universal, bukan Barat dan bukan Timur. ”Dan siapa yang tak mengikutinya dengan seksama akan seperti orang buta melihat bumi.” Bukan cuma ajaran science yang, kalau perlu, harus diambil dari luar. Dalam ”Al-e-Ahmad”, dengan sensitif Goenawan menggambarkan pergulatan seorang intelektual Iran ‘’dengan pelbagai sikap dan pelbagai pemikiran dari pelbagai penjuru.” Lebih jelas lagi, ”dendam” mempertentangkan peradilan Inggris di Singapura pada zaman Raffles yang, dengan adat Melayu, memvonis mati seorang pembunuh, yang menghukum mati seluruh keluarga dan sanak saudara si pembunuh. Keluh Goenawan, ”di zaman ini pun kita masih mempersoalkan dari mana datangnya hukum… bukan baik buruknya hukum itu.”
***
PENOLAKAN Goenawan terhadap pengkotakan TimurBarat juga sangat kentara dalam cara kerjanya, cara dia mencari materi dan ilham, yang sama sekali tidak mengenal batas ruang dan waktu. Tema-tema tulisannya ia kembangkan dengan contoh dan cerita dari Italia dan Yunani Kuno, Rusia dan Prancis sebelum dan pada masa revolusi, Jepang, Cina, Eropa, dan Amerika dewasa ini, serta tentu saja dari Indonesia, tempat ia antara lain terpesona pada tokoh dari dunia pewayangan. Semua unsur ini saling mempengaruhi, saling menganyam, seakan-akan tidak perlu membuat batas antara yang Indonesia dan yang bukan Indonesia, antara yang Timur dan yang Barat.
Di belakang pendekatan ini terlihat suatu pegangan yang sangat mendasar mengenai hubungan antara apa yang sekarang lazim disebut ”kultur” dan ”struktur”, atau ide dan kepentingan. Menurut Goenawan, pada akhirnya sebuah ide mustahil diangkat, diabstraksikan, dari lingkungan konkretnya di dunia nyata. Setiap ide yang dilepaskan dalam masyarakat akan tumbuh, berkembang, dan berubah sesuai dengan interaksinya dengan kepentingan dan kejadian dalam ruang dan waktu, pendeknya dengan sejarah (”Remigio”). Timur dan Barat adalah contoh abstraksi yang menyesatkan, yang tidak membantu pengertian kita tentang masyarakat Indonesia, sebab tidak mempunyai referensi konkret yang jelas.
Kalau lahan yang digarapnya begitu universal, mengapa tadi saya katakan bahwa Goenawan sudah memiliki rumah, tegasnya bahwa rumah dia adalah budaya nasional-Indonesia? Ia tidak secara eksplisit membicarakan bentuk dan isi budaya nasional. Lagi pula, menangkap tujuan dan makna prosanya tidak selalu mudah. Sebagai seorang esais—yang berjiwa penyair—dia belum pernah merumuskan pikirannya dalam satu atau beberapa tulisan pokok. Inti persoalan yang diungkapkannya setiap minggu sering dibungkus dalam cerita yang memikat tetapi rumit, dan disajikan dengan gaya yang menawan tetapi melayang.
Namun demikian, saya percaya bahwa pembaca yang tekun dan teliti akan menemukan sebuah pemandangan yang khas Indonesia. Pemandangan itu berkali-kali menjelma sebagai perbenturan hak tiap individu untuk membentuk jati dirinya dengan kecenderungan setiap pemerintahan, khususnya di Dunia Ketiga, yang membatasi hak itu.
Perhatian Goenawan kepada individu tecermin dalam beberapa Catatan Pinggir mengenai perjuangan seseorang untuk berbuat sesuatu, termasuk orang besar seperti Oedipus (”Oedipus”), Van Gogh (”Kanvas”), Chairil Anwar (”Jepang” dan ”Chairil”), atau Muhammad Radjab (”Pemberontakan Radjab”), dan orang kecil seperti tukang cukur di Jakarta (”Burhan”) atau penarik becak di Bandung (”The Death of Sukardal”). Tetapi yang paling menunjukkan komitmennya kepada insan manusia sebagai titik dasar dan alat ukur segala aturan sosial dan politik adalah ”Koppig (baca: Kopekh)” dan ”Sidis”.
”Koppig” menceritakan percakapan imajiner di antara beberapa orang dengan pandangan yang berbeda—pamong desa, pejabat, mahasiswa, rohaniwan, wartawan—mengenai nasib rakyat kecil yang rumah dan tanahnya tengah terancam oleh sebuah bendungan. Yang penting, kata Goenawan, jangan sampai terlupakan bahwa ”bagaimanapun rakyat tak bisa dihilangkan haknya—yang diberikan Tuhan—untuk memilih jalan hidup sendiri.” Lagi pula, orang yang berpretensi lebih tahu apa yang baik bagi rakyat ketimbang rakyat sendiri diingatkan: ”hati dan perasaan sering punya pilihan dan ungkapannya sendiri. Tak selalu mudah kita memahaminya, tak selalu mudah kita mengkalkulasikannya.”
Pelajaran yang bisa diambil dari ”Sidis” barangkali lebih fundamental lagi. William Sidis, seorang jenius yang masuk Harvard pada umur 11 tahun, meninggal pada usia muda dalam keadaan sengsara tanpa prestasi apa-apa. Masa kecilnya disita oleh ayahnya, yang ingin membuatnya menjadi contoh bagaimana pembimbingan yang ketat dan terarah bisa menghasilkan manusia yang lebih sempurna. Pendidikan inkonvensional ini gagal sebab tidak mendidik William untuk berpikir dan berdiri sendiri. ”Manusia memang bisa dikarbit, dicetak, diarahkan—siapa bilang tidak. Tapi kelak, akhirnya krisis akan menembak kita sebagai kita sendiri. Tanpa proteksi.”
Goenawan mengharapkan dan menuntut banyak dari manusia yang merdeka dan mandiri. Sastrawan akan menjadi lebih kreatif, malah akan mendorong bagian masyarakat lain untuk maju: ”dengan bentrokan, juga dialog, di antara kedua dunia itulah sejarah berkembang” (”Burhan”). Pembangunan ekonomi akan lebih berhasil kalau didasarkan pada pasar bebas yang betul-betul kompetitif, yang membuka ruang gerak bagi inovasi dan orang yang bersedia kerja keras. Dan kerja keras itu, ditegaskannya beberapa kali, merupakan persyaratan bagi setiap masyarakat yang ingin berprestasi: ”kerja—dalam sejarah—telah melahirkan peradaban” (”Manekin”).
Jenis pemerintahan yang cocok dengan konsepsi manusia tersebut adalah demokrasi perwakilan yang memberi rakyat kebebasan membentuk dirinya sendiri. Kebebasan itu dilindungi oleh jaminan hak-hak asasi dan proses pemilihan umum, yang mengharuskan wakil-wakil rakyat di badan legislatif dan eksekutif bertanggung jawab kepada para pemilih. Demokrasi juga dibutuhkan untuk menciptakan solidaritas sosial, supaya seluruh rakyat merasa ikut serta sebagai anggota penuh negara kebangsaan mereka.
***
MENGGAMBARKAN pemilu tahun 1987, yang kebetulan saya amati juga ketika menjadi dosen tamu di Banda Aceh, Goenawan menulis, ”lima tahun sekali, setidaknya, orang-orang penting pada menatap rakyat dengan sedikit lebih cermat. Dan seluruh Indonesia pun dipertautkan lagi…. Dalam suatu momen yang agaknya jarang terjadi, mereka seakan-akan secara bergelora merasakan, ke ulu hati, bahwa Indonesia—Indonesia yang besar ini—adalah bagian hidup mereka” (”Ah, Rakyat”). Kiranya tidak sulit membaca emosi mendalam yang tersirat dalam kalimat itu.
Sayangnya, mendirikan dan mempertahankan demokrasi di Dunia Ketiga, termasuk Indonesia, ternyata tidak mudah. Para pemimpin politik kebanyakan negara bekas jajahan Eropa di Asia dan Afrika meninggalkan demokrasi beberapa tahun setelah mereka mencapai kemerdekaan. Mereka menggantikannya dengan jenis-jenis pemerintahan yang sangat bergantung pada kepemimpinan seseorang, kepercayaan pada ideologi, atau kekuatan hierarkis birokrasi sebagai dasar kekuasaannya. Sebagian besar Catatan Pinggir dalam kumpulan ini membicarakan hal tersebut, baik ciri maupun sebab musababnya.
Membaca buah pikirannya mengenai kekuasaan pribadi dan ideologi, saya lalu teringat bahwa Goenawan mengalami pendidikan politiknya (kalau saya boleh menggunakan istilah yang begitu kering) yang pertama pada zaman Orde Lama. Kala itu Presiden Sukarno masih berada di atas segala-galanya dan PKI sedang mengganas dengan desakan ideologinya yang makin hari makin seru. Nun jauh di Pematang Siantar, tempat saya waktu itu sedang melakukan penelitian mengenai partisipasi politik, saya juga merasa bingung dan was-was mengenai masa depan teman-teman saya. Jadi tidak sulit bagi saya untuk mengerti kalau soal-soal itu nyaris menjadi obsesi bagi Goenawan dan generasinya.
Kekuasaan pribadi digambarkan sebagai jenis pemerintahan yang memisahkan pemimpin dan masyarakat. Berbagai otokrat dan berbagai zaman dan negara diceritakan sebagai biadab, sewenang-wenang, rakus, manipulatif, tidak bertanggung jawab, berkepentingan pribadi, korup, dan seterusnya. ”Untuk jadi seorang otokrat besar kita harus jadi seorang biadab besar” (”O, Absyalom”). ”Kekuasaan itu… ibarat katak hendak jadi lembu: mau mengatur segalanya, menaklukkan segalanya…” (”Babilon”). ”Sebuah negeri yang diperintah oleh satu orang bukanlah sebuah negeri sama sekali” (”Terbuka”).
Pahlawan yang bukan pemimpin negara pun dicurigai, dan kita diingatkan betapa mereka semua adalah manusia biasa dengan segala kebaikan dan keburukannya. Bahwa pada akhirnya sang diktator pasti mati, dan seluruh sistem kekuasaannya akan ambruk, menjadi alasan kuat bagi Goenawan untuk menolaknya. Tetapi menarik untuk dicatat, Soekarno sendiri dilukiskannya sebagai seorang pemimpin negara yang kompleks dan penuh kontradiksi (”Bung Karno (1)”.)
Ideologi disoroti Goenawan sebagai sesuatu yang mencekik leher masyarakat, yang mencegah pertumbuhan ide-ide baru dan perkembangan manusia yang otentik, yaitu merumuskan cara dan gaya hidup sendiri. Berkali-kali ia mengecam ideologi dengan kata-kata yang tajam dan penuh kemarahan. ”Upaya besar totaliter: orang banyak yang digerakkan dalam barisan” (”PKI”). ”Militansi membutuhkan beberapa anasir: kepekatan hati untuk fanatik dan kesiapan pikiran untuk menyederhanakan soal” (”Cicak”). ”Kejahatan besar dilakukan dengan organisasi kenegaraan yang lebih besar, dan ideologi-ideologi yang kukuh mendukungnya” (”Sang Brahmana”).
Di belakang ideologi sering terdapat revolusi. Sebagai orang Indonesia pascakolonial, Goenawan tentu mewarisi keberhasilan pergerakan nasional dan revolusi kemerdekaan. Tetapi dia maklum juga bahwa setiap revolusi menuntut biaya: ”Tradisi kaum revolusioner Rusia—yang kemudian ditiru di mana-mana, dan tak cuma oleh orang komunis—ialah bahwa kepatuhan pada doktrin adalah lambang kesetiaan, dan berbeda pendapat adalah pengkhianatan” (”Sang Komunis”).
Beberapa Catatan Pinggir mencela birokrasi. Salah satu kelemahan birokrasi, di negara tempat tidak ada kekuatan lain yang bisa mengimbanginya, adalah kecenderungannya untuk korupsi. ”Korupsi ialah kanker yang akhirnya mengeremus harapan dan kepercayaan” (”Korupsi”). Lagi pula, para birokrat takut pada chaos yang mereka anggap satu-satunya alternatif bagi sebuah orde ”yang tegak, dingin, kompak seperti tembok rumah Belanda” (”Biro”). Dan mereka kacaukan kepentingan umum dengan kepentingan pribadi, sambil menyangkal bahwa mereka punya kepentingan pribadi. ”Betapa nonsens…,” kata Goenawan (”Nonsens”).
Kekuasaan pribadi, dominasi ideologi, dan birokratisasi adalah hal-hal yang seharusnya dihindari, tetapi terdapat dimanamana, khususnya di Dunia Ketiga. Mengapa? Salah satu jawaban Goenawan adalah, kita hidup di dunia yang serba tidak tentu dan, oleh karena itu, menakutkan. ”Di dunia kini ada negeri-negeri yang terguncang, oleh revolusi ataupun oleh kelahiran diri yang mendadak…. Dan orang gelisah, mengikuti ini mengikuti itu, dan mencari patokan perilaku” (”Khomeini”).
Setelah revolusi kemerdekaan selesai, ketika tidak ada lagi proses ”yang menggetarkan hati, menyebabkan bulu roma berdiri, dan perasaan terharu” (”Gerhana”), kekosongan batin menjadi gejala umum. Bagi banyak orang, mengisi kehampaan itu dengan perpolitikan demokratis, yang bersifat persaingan pribadi dan tukar-menukar dukungan dan jasa, tidak memuaskan, malah memuakkan”…: 40 tahun yang lalu… orang benar-benar sedang berjuang. Bukannya sedang meyakin-yakinkan diri bahwa ia sedang berjuang” (”Cengeng”). Jadi di beberapa negara lahirlah ”seorang pemimpin yang dituntut untuk jadi komplet” (”Khomeini”).
Sebetulnya, bagi Goenawan ketidaktentuan adalah ciri umum manusia, bukan hanya gejala masa kini di Dunia Ketiga. ”Kebenaran itu ibarat cicak,” kutipnya dari penulis Rusia Turgenev. ”Yang kita tangkap selalu cuma ekornya, yang menggelepar seperti hidup—sementara cicak itu sendiri lepas” (”Cicak”). Moralitas pun tidak luput dan kenisbian: ”ada hal-hal di dalam hidup yang memang tak hanya punya satu jawaban” (”E”). Dan, mengutip filosof Inggris Isaiah Berlin, ”Nilai-nilai bisa dengan mudahnya berbenturan dalam dada seorang individu … dan jika itu terjadi, tak berarti bahwa sebagian benar dan yang sebagian lagi salah” (”Gerhana”).
***
KIRANYA jelas bahwa Goenawan sangat meyakini demokrasi sebagai jenis pemerintahan yang terbaik bagi negara kebangsaan Dunia Ketiga seperti Indonesia. Tetapi dia tidak berpretensi seolah-olah demokrasi dengan sendirinya mampu menyelesaikan segala persoalan. Paling tidak, ada empat hal yang diakuinya masih menjadi tanda tanya.
Yang pertama adalah bagaimana mewujudkan demokrasi di negara yang belum demokratis. Di negeri saya ada ilmuwan politik yang sudah yakin bahwa mereka punya teori mujarab untuk demokratisasi, tetapi Goenawan (dan saya) bersikap lebih hatihati. Dalam {”Parlemen” dan ”Demokrasi (1)”} dia mengejar rahasia demokratisasi dalam sejarah Inggris, Amerika, dan Prancis yang berliku-liku dan mengandung banyak unsur kebetulan.
Kesimpulannya, demokrasi ”tak bisa dipesan sekaligus, seperti kalau kita memesan nasi bungkus.” Akan tetapi, ”Barangkali demokrasi adalah satu demam yang menular.” Dalam ”Deng, Ding, Dong” nadanya hampir sama; ”Mungkin demokratisasi tak memerlukan teori. Saya kira, demokratisasi hanya memerlukan kebutuhan. Atau juga tekad….”
Dari mana datangnya kebutuhan dan tekad? Jawabannya masih samar, tetapi yang ditekankan beberapa kali adalah hakikat manusia sebagai ciptaan Tuhan. Misalnya, ”Hog” bercerita tentang seorang hakim korup di Romawi pada abad terakhir sebelum Masehi. Hog akhirnya dikalahkan, karena masyarakat menuntut pada hakim mereka sesuatu yang lebih dari etika ”resiprositas” yang kotor, ”karena di alam semesta ini ada yang memancarkan kebaikan, keadilan dan kebenaran, sebuah sumber yang mahapemberi, yang… memberikan keputusan yang final.”
Hal kedua yang menjadi tanda tanya adalah pertentangan yang umum terdapat di negara demokratis antara passion, gelora hati, dan kepentingan. Tanpa menyadari sepenuhnya, Goenawan (seperti mungkin kebanyakah pengagum demokrasi) menduahati mengenai hal ini. Berkali-kali dia mengisahkan betapa buruknya gelora hati, yang sulit dibendung dan sering menghanyutkan kebebasan individu. Dan dia mengutip dengan memuji seorang teman bekas demonstran yang berkata, ”Kepentingan, atau interes, telah mengepung gelora hati” (”Passion”).
Pemerintahan demokratis, yang justru berdasarkan kepentingan, tentu didukung, tetapi juga disangsikan sebab kadang kala mendekati ”sebuah lomba penampilan pribadi” (”Politik”) dan tidak mampu mengilhami orang untuk berbuat dengan dedikasi dan komitmen yang tinggi. ”Karena akhirnya orang toh ingin mencari tujuan hidup, satu makna, dan bukan cuma status dan benda-benda?” (”Naro + Hampa”).
Untuk mengobati penyakit ini, resep yang ditawarkan Goenawan adalah gelora hati! Dia mengutip, lagi-lagi dengan memuji, Hegel: Tak ada hal besar di dunia ini telah tercapai tanpa passion (”Fan”). Dan ternyata kepahlawanan masih diperlukan pula, umpamanya dalam kasus Martin Luther King (”Drama”), dr Hwang yang membuka rahasia rezim Chun Doo-Hwan (”Hwang”), dan Yudistira (”Kalpataru”).
Ketiga, terlihat ketegangan antara keyakinan Goenawan mengenai ketidaktentuan dunia dan kepercayaannya pada dampak positif tindakan-tindakan politik. Di sini juga saya kira Goenawan mewakili keragu-raguan banyak pemikir politik di mancanegara. Membaca beberapa Catatan Pinggir, seperti ”Hwang” dari Korea, ”yang telah mengangkat bangsa itu ke suatu taraf yang lebih tinggi”, saya merasa dibawa ke puncak harapan. Dalam hal lain, ”Koppig” dan ”The Death of Sukardal” menceritakan kegagalan tetapi juga mengandung harapan untuk masa depan. Walaupun mati, Sukardal, si tukang becak yang kehilangan sumber nafkah dan gantung diri, ”tidak membisu. Dan hidup kita… terbuat dari kematian orang-orang lain yang tidak membisu.”
Tetapi Catatan Pinggir lain menyeret saya ke lembah keputusasaan. Misalnya, ”Deng, Ding, Dong” yang menegaskan bahwa kita tidak memiliki ”teori politik untuk transformasi negeri-negeri berkembang.” Oleh sebab itu, kita ragu-ragu mengecam Deng ketika dia membela tindakan kejinya di Tiananmen sebagai bukti keberanian dia untuk bertindak demi keselamatan revolusinya.
Meskipun tahu, Macbeth tidak dapat mengelakkan nasibnya (”Macbeth”). ”Apakah artinya, kemudian, kebebasan dan kekuasaan manusia untuk menentukan nasib sendiri, ketika nasib tak pernah bisa ditentukan sendiri?” Dan Wibhisana membantu Rama melawan Rahwana untuk menegakkan kebenaran atau, paling sedikit, supaya ”seorang pemenang pun akan bisa tahu kerendahan hati.” Tetapi yang terjadi justru sebaliknya: perasaan-perasaan sederhana mehjadi mustahil dan kecintaan terkuras dari hati Rama (”Wibhisana”).
Tanda tanya yang keempat menyangkut keserakahan manusia dan hubungannya dengan demokrasi. Rezim ekonomi yang cocok dengan demokrasi, juga dengan kebebasan individu, adalah rezim pasar. Goenawan menghargai prestasi ekonomi yang dicapai oleh Jepang dan negara-negara Barat, dan dia sadar bahwa golongan revolusioner yang sejati dalam sejarah Eropa adalah kaum wiraswasta, bukan buruh. ”Melahirkan borjuasi… berarti melepaskan sebagian besar masyarakat dari kontrol, untuk berkembang dengan motivasi sendiri dan tujuan sendiri” (”Rong”). Tetapi dia juga percaya bahwa di sana etika puritan—kerja keras dan hidup sederhana—sebagian sudah diganti dengan etika hedonis—kerja santai dan hidup mewah.
Apakah ada kebijaksanaan ekonomi yang bisa sekaligus mencapai pertumbuhan dan pemerataan? Jawaban Goenawan tidak menyelesaikan persoalan, tetapi menurut saya menempatkan kita pada jalan yang benar. ”Mungkin kita harus mengakui keniscayaan keserakahan manusia… lalu kita bikin sistem yang bisa jalan—yang menyebabkan keserakahan manusia tak menjadi destruktif” (”Burma”). Saya hanya ingin menambahkan, meskipun mungkin tidak terlalu penting, bahwa bagi saya persoalannya bukan keserakahan manusia pada umumnya, melainkan keserakahan sebagian manusia yang relatif kecil. Namun tentu masih harus disertai penciptaan sistem korektif yang tepat.
***
SEBAGAI kata penutup, saya ingin kembali ke tema pokok saya, yaitu bahwa Goenawan Mohamad adalah seorang penulis yang berkebudayaan Indonesia akhir abad ke-20. Dalam hampir 160 Catatan Pinggir ini, berikut ratusan Catatan Pinggir dan karangan lain yang sudah ditulisnya selama dua dasawarsa terakhir ini dalam majalah Tempo, dia telah menggali pengalaman dunia guna menjawab tantangan yang dihadapi bangsanya masa kini.
Tantangan itu, menurut Goenawan, adalah bagaimana, pada zaman modern dan pascarevolusi, menciptakan kondisi sosial, ekonomi, dan khususnya politik, untuk mewujudkan manusia Indonesia yang merdeka dan mandiri. Jawabannya tegas tapi tidak tuntas, dan memang tidak mungkin tuntas. Tidak ada jenis pemerintahan, termasuk demokrasi, yang mampu memecahkan segala persoalan yang hadir di tengah masyarakat besar dan majemuk; tidak ada jenis pemerintahan, termasuk demokrasi, tanpa kekurangan dan cacat bawaan.
Apa sumbangan Goenawan kepada perkembangan budaya nasional Indonesia? Ringkasnya, dengan argumen-argumen yang meyakinkan, dia menolak kerangka pengkotakan Timur-Barat yang sudah usang tetapi masih umum dipakai, mengangkat si individu sebagai tujuan pokok dan tolok ukur kemajuan bangsa, memilih demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang terbaik, dan merumuskan beberapa problem yang menghalangi perwujudan demokrasi tersebut. Halangan-halangan itulah yang seharusnya menjadi fokus perhatian dan renungan para pemikir dan negarawan sekarang.
—————————————————————————
*Tulisan ini adalah “Pengantar” pada buku Catatan Pinggir 3 , Goenawan Mohamad, Pusat Data dan Analisis Tempo, 2012