Oleh Rofinus Pati
Modernitas merupakan zaman di mana manusia mendewakan ilmu pengetahuan, teknologi dan akal budinya di dalam memahami pelbagai hal, termasuk masyarakat. Hal-hal yang bersifat mistik atau gaib dalam masyarakat berusaha dijelaskan secara memadai oleh ilmu pengetahuan, teknologi dan akal budi manusia. Manusia di era modern pun menganggap masyarakat seperti sebidang tanah baru dan akan dirawat serta diolah sesuai tujuan yang sudah dirancang oleh manusia sendiri.
Zygmunt Bauman (1925-2017), seorang pakar ilmu sosial asal Polandia, menjelaskan modernitas sebagai “an age of ‘gardeners’ who treat society as a virgin plot of land expertly designed and then cultivated and doctored to keep to the design form” (Bauman 1989:113). Masyarakat tidak hanya merupakan kelompok sosial yang dipahami, melainkan menjadi sarana untuk menemukan makna atau nilai-nilai baru dalam terang akal budi manusia.
Bauman membahas dua konsep atau gejala pokok tentang modernitas. Kedua konsep itu adalah modernitas padat (solid modernity) dan modernitas cair (liquid modernity). Menurut Bauman, modernitas padat ditandai oleh masyarakat yang bertumbuh dan berkembang, berpedoman pada ide, tatanan, ‘statusquo’, norma-norma, tradisi, aturan, sistem dan semacamnya.
Sebaliknya, modernitas cair (liquid modernity) mengacu kepada masyarakat yang dikendalikan oleh perubahan terus-menerus dan perubahan itu berlangsung cepat. Perubahan ini membuat ide, tatanan, tradisi, sistem dan semacamnya, tidak lagi merupakan dasar-dasar yang kokoh untuk menjadi pedoman moral maupun panduan dalam tindakan nyata.
Sekolah dan Peserta Didik
Tulisan ini bertolak dari satu pemahaman bahwa sekolah dan semua ‘stakeholder’ yang berkecimpung di dalamnya merupakan sebuah kelompok sosial yang bergerak di bidang pendidikan untuk mencerdaskan dan mengadabkan anak bangsa. Selain sebagai kelompok sosial mini, sekolah juga adalah sebuah tatanan, institusi, yang jauh di tahun-tahun sebelum Covid 19, tergolong dalam modernitas padat (solid modernity).
Menurut Bauman, “solid modernity is characterized by structure, predictability and enduring institution. Individuals were embedded in fixed social roles and institution, such as family, work and community. These structures provided a sense of security and belonging” (easysociology.com, Januari, 14, 2024). Tidak perlu dijelaskan lagi bahwa sekolah sebagai lembaga pendidikan, dalam konteks modernitas padat (solid modernity), merupakan sebuah tatanan.
Sebagai tatanan, sekolah memiliki peraturan dan tata tertib baku, pola tingkah laku dan nilai-nilai lokal maupun universal yang menjadi pedoman bagi setiap individu atau insan pendidikan. Ada tata tertib bagi peserta didik, aturan bagi para guru/pegawai tata usaha maupun tenaga layanan khusus lainnya.
Setiap orang sebagai rekan kerja, menjadi bagian tak terpisahkan dari sekolah dan tunduk di bawah peraturan atau tata tertib sekolah. Ada disiplin dan nilai-nilai hidup bersama yang harus dipatuhi sehingga terhindar dari tindakan indisipliner. Siapa yang melanggar tata tertib dianggap berada di luar sekolah sebagai sebuah tatanan.
Sekolah dalam konteks modernitas merupakan “the big other” (Myers 2003:35) dan memiliki otoritas. Tuntutan sekolah dalam bentuk regulasi menagih kepatuhan dari setiap anggota lembaga pendidikan. Kepatuhan juga memunculkan keberadaban yang ditunjukkan lewat sopan-santun, hormat, terutama peserta didik kepada para guru atau rekan kerja yang lebih tua maupun sebaya.
Dengan perkataan lain, pada masa “solid modernity”, setiap peserta didik mengidentikkan dirinya dengan sekolah sebagai institusi dan mematuhi regulasi untuk menghindari sanksi sebagai konsekuensi logisnya. Harmoni dan “kemapanan” tercipta, sebab peserta didik memahami tempatnya dalam sistem dan menunjukkan sikap-sikap terpuji atau akhlak mulia kepada orang-orang dalam institusi. Sekolah dapat menjamin dua hal pada peserta didik yakni rasa aman (feeling of security) dan rasa memiliki (sense of belonging) yang akan menunjang pelbagai aktivitas lainnya.
Hal ini ditunjukkan dalam beberapa fakta yang cukup dialami, dirasakan oleh peserta didik pada masanya (termasuk penulis sendiri) di sekolah-sekolah kampung dan setingkat kabupaten :
Pertama, jauh-jauh tahun sebelum Covid 19 dan ketika teknologi atau media digital belum membanjiri sekolah di kampung-kampung, para peserta didik dalam tatanan sekolah dengan konteks “solid modernity”, menunjukkan sikap hormat dan sopan santun terhadap para guru/pegawai, baik dalam tutur kata maupun perilakunya.
Misalnya, ketika berpapasan dengan para guru pada jarak sekitar delapan atau sembilan meter, para peserta didik sudah berlomba-lomba menyampaikan salam dengan posisi badan sopan, agak merunduk. Ada perasaan hormat dan sungkan pada guru-guru. Saban hari, setiap peserta didik membawa seberkas kayu bakar untuk guru-gurunya, menimba air mengisi wadah di rumah guru hingga penuh, bahkan mencabut rerumputan di kebun yang digarap guru-gurunya sehingga padi atau jagung bisa leluasa bertumbuh, dan lain-lain lagi.
Kedua, media pembelajaran masih menggunakan buku tulis dengan kewajiban mencatat atau menulis bagi para peserta didik, sehingga ada keseriusan untuk belajar dan pembelajarannya mendalam. Setiap peserta didik memastikan diri untuk memiliki alat tulis dan memiliki buku-buku catatan lengkap. Hal ini didukung lagi dengan semangat belajar tinggi dari pihak peserta didik. Keseriusan dalam belajar menjadi ciri khas umum peserta didik, sebab aktivitas lain tidak terkontaminasi oleh teknologi atau media digital seperti sekarang ini.
Di era itu, menjadi pemandangan umum bahwa peserta didik memiliki buku catatan tebal-tebal, dengan peralatan tulis lengkap yang setia dipikul ketika hendak pergi ke sekolah atau kembali ke rumah. Lebih dari itu, tas sekolah barangkali merupakan barang mahal kala itu dan hanya segelintir peserta didik yang mampu membelinya. Namun, kantong plastik setia mengisi semua buku dan peralatan tulis serta melindunginya dari air hujan.
Ketiga, atmosfir dan ikatan komunal amat terasa dalam kehidupan peserta didik. Kebersamaan peserta didik, selain di sekolah dan berjalan pulang ke rumah, biasanya diwujudkan dalam belajar kelompok di rumah, asrama, pada sore maupun malam hari.
Perjumpaan langsung dan interaksi antarteman sebaya, menambah ikatan sosial di antara para remaja. Belajar bersama, berbagi keceriaan dalam suasana saling mendukung, mampu menghalau perasaan teralienasi dari peserta didik dan sesamanya sebagai remaja, saling meneguhkan dalam belajar untuk meraih masa depan yang lebih baik.
Keempat, motivasi hidup dan daya juang tinggi, terkhusus dalam belajar dan bekerja untuk meraih hasil maksimal. Kebersamaan nyata menjadi daya dorong bagi para remaja di dalam belajar dan menjalani keseharian hidup. Optimisme terbentang antara kenyataan dan harapan, karakter dan kepribadian cukup matang. Bermodalkan motivasi dan daya juang tinggi, pelbagai masalah dapat dihadapi dan diatasi tanpa harus berlari daripadanya atau memilih jalan pintas.
Peserta Didik Lentur, Modernitas Mengalir
Sudah diutarakan pada awal tulisan ini bahwa modernitas padat (solid modernity) memiliki satu kekhasan yakni kuatnya peran “the big other” (baca: sekolah atau para guru). Sekolah sebagai sebuah tatanan dan “the big other” mengelola dan mengendalikan segenap ‘stakeholder’ terkait, terkhusus dalam pembahasan ini yakni peserta didik.
Namun, Bauman, seperti halnya Giddens dan Foucault, menegaskan bahwa modernitas cair (liquid modernity) pada dasarnya memunculkan praktik-praktik yang menantang lembaga-lembaga modern (Lee 2005:63). Modernitas cair ditandai juga oleh fakta bahwa peran-peran dari “the big other” semakin merosot drastis (Meyers 2003:35).
Modernitas cair menyebabkan kehidupan setiap hari pun menjadi cair. Kehidupan cair terjadi di dalam masyarakat cair, yang ditandai oleh perubahan terus-menerus dan ketidakpastian permanen (constant uncertainty). Perubahan dan ketidakpastian ini pula melanda peserta didik di dalam dunia pendidikan, sebab keempat poin dalam modernitas padat (solid modernity) yang dipaparkan di atas mengalami perubahan dan dapat dideskripsikan sebagai berikut:
Pertama, para guru di era teknologi dan media digital seperti sekarang ini, barangkali ke depan semakin sepi dari perhatian dan rasa hormat dari peserta didik. Bukan berarti peserta didik tidak mau menunjukkan rasa hormat atau sopan santun, melainkan peserta didik semakin tekun dan mengalihkan perhatian ke media digital, menciptakan dunianya sendiri dan merasa nyaman, bahkan ketagihan dengan kenyamanan semu itu.
Selain itu, profesi guru bukanlah profesi perintis seperti angkatan Ki Hajar Dewantara atau sesudahnya, sehingga menjadi profesi primadona pada zaman itu. Sudah banyak profesi yang berkembang sampai saat ini, sehingga posisi guru hanyalah salah satu di antara banyak profesi lainnya.
Peserta didik tidak seratus prosen membutuhkan guru seperti dahulu di kampung-kampung, sebab jaringan internet dan media digital dapat menjadi guru maya, yang daripadanya peserta didik dapat belajar lebih banyak ilmu pengetahuan dan ketrampilan, kapan dan di mana saja. Waktu dan ruang kelas pun menyusut, guru yang adalah manusia nyata, terasa lebih jauh dari jari tangan peserta didik dan layar kaca di hadapannya.
Kedua, Bauman sendiri menyatakan bahwa setiap anggota masyarakat selalu dipacu untuk berubah terus-menerus setiap waktu. Dengan demikian, apapun yang dilakukan tidak dapat bersifat tetap dan menjadi rutinitas atau kebiasaan, sebab kehidupan pribadi maupun masyarakat senantiasa cair, bergerak, berubah tiada henti. Apa yang selalu terjadi adalah perubahan.
Bauman sendiri mengatakan: … a society in which the conditions under which its member act change faster than it takes the way of acting to consolidate into habits and routines. Liquidity of life and that of society feed and reinvigorate each other. Liquid life, just like liquid modern society cannot keep its shape or stay on course for long (Bauman 2005:1)
Hal ini terjadi juga pada peserta didik yang adalah remaja di era digital. Pembelajaran dahulu dengan media buku tulis dan menggunakan alat tulis untuk mencatat atau menulis, kini berubah ke media digital. Pembelajaran semakin santai yang terbawa sejak masa Covid 19, membuat bobot studi menjadi dangkal, hanya melata di permukaan, karena tidak serius. Juga perubahan lainnya.
Beberapa kenyataan pada level SMP dan SMA di kampung dapat diangkat sebagai misal. Ketika sistem pembelajaran dan ujian di sekolah berbasis komputer dan android, maka kertas-kertas dan alat tulis tidak lagi dibutuhkan. Patut diakui bahwa banyak anak ditemukan tidak mempunyai catatan di buku tulis. Peralatan tulis pun tidak dimiliki, bahkan saat ujian ketika harus mencakar pada kertas buraman.
Tanpa disadari, sistem pembelajaran daring (online) pada masa Covid 19 membawa dampak besar sampai sekarang yakni sikap santai. Banyak peserta didik santai dalam belajar dan bekerja, namun menginginkan, bahkan menuntut hasil maksimal dalam situasi dan arus informasi yang selalu berubah. Ini menyuburkan mentalitas instan pada diri peserta didik, sehingga menyontek di ‘handphone’ saat ujian.
Untuk itu, ada benarnya ketika ada negara maju yang sudah meninggalkan media digital dan kembali kepada buku, mewajibkan peserta didik membaca dan menulis tangan, sebab kegiatan menulis menggunakan tangan akan meninggalkan goresan di dalam buku dan membekas dalam kepala. Aktivitas tangan yang menulis terhubung langsung ke otak melalui saraf. Hal ini membuat peserta didik lebih mengingatnya dalam otak dibandingkan mengetik atau membaca di layar kaca.
Ketiga, Bauman sendiri melihat ada keanehan pada modernitas cair. Ada pertentangan di dalamnya. Rasa kebersamaan, saling mendukung dan interaksi langsung di antara peserta didik dalam konteks modernitas padat terdahulu, kini sudah terkikis, sehingga memunculkan individualisme. Sayangnya, individu ditonjolkan, namun individu tidak bebas menentukan pilihan. Pilihan atas tawaran dari media digital sudah ditentukan dan individu hanya mengikuti, menikmatinya. Pilihan itu bisa saja tidak baik, tidak benar dan tidak berguna.
Dengan kata lain, peserta didik (yang hanya karena tersandra di dunia maya atau media digital) sudah meninggalkan kebersamaan dan interaksi langsung di dunia nyata, harus mengalami kesulitan atau kebingungan moral.
Peserta didik dihimbau untuk melakukan sesuatu yang baik, benar dan berguna, namun pada saat yang sama, peserta didik melihat dan mengetahui bahwa pedoman etis untuk melakukan yang baik, benar dan berguna dilanggar seenaknya atau tidak dijalankan sama sekali. Apalagi yang melanggarnya adalah pihak-pihak yang sepatutnya menjadi panutan. Inilah paradoks yang dilihat Bauman.
“The ethical paradox of the postmodern condition is that it restores to agents the fullness of moral choice and responsibility while simultaneously depriving them of the comfort of the universal guidance that modern self-confidence once promised. Ethical task of individuals grow while the socially produced resources to fulfil them shrink. Moral responsibility comes togetherwith the loneliness of moral choice” (Bauman 1992: xxii).
Modernitas cair ditandai oleh kecepatan dan perubahan terus-menerus. Selain itu, modernitas cair juga memiliki tingkat ketidakpastian tinggi, sehingga setiap peserta didik harus menyesuaikan diri dengan perubahan. Namun demikian, paradoks etis bisa muncul ketika landasan atau pedoman moral-etis goyah atau diabaikan oleh pihak yang bertanggung jawab. Dan ini bisa menimbulkan distorsi atau disorientasi pada diri peserta didik.
Bagaimana harus bertanggung jawab kepada peserta didik, kalau mereka dihimbau untuk tidak menipu misalnya, tetapi pada saat yang sama peserta didik menyaksikan masyarakat sekitar (bahkan di rumahnya sendiri) menganggap menipu sebagai hal yang biasa saja? Bagaimana peserta didik tidak bingung, jika dinasihati untuk tidak mengeluarkan perkataan kotor, tetapi di rumah atau lingkungannya sendiri, kata-kata kotor itu merupakan langganan tetap di mulut?
Bagaimana peserta didik dikotbahi untuk tidak mencuri dalam dunia yang berubah terus-menerus dan cepat ini, tetapi kenyataannya mereka membaca dan mengetahui bahwa korupsi sulit dihapuskan, bahkan dibanggakan? Bagaimana peserta didik tidak mengalami kebingungan, sebab dilarang berbuat cabul, namun di dunia maya, mereka digempur habis-habisan oleh tontonan-tontonan yang hanya patut untuk ruang privat? Dan seterusnya.
Keempat, pada masa modernitas cair ini, motivasi dan daya juang peserta didik umumnya masih cukup rendah, khususnya dalam belajar bersama dan kerjasama untuk meraih hasil yang maksimal. Sikap santai seperti rantai yang belum dapat diputuskan sejak belajar dari rumah di musim Covid 19, menghalangi kesempatan bagi peserta didik untuk belajar secara serius dan membuat target jelas di masa depan. Barangkali kebijakan Mendikdasmen Prof. Dr. Abdul Mu’ti hendak mengatasinya dengan program “deep learning atau meaningful learning” saat ini.
Sikap santai peserta didik ini, diperparah lagi karena ketagihan peserta didik dalam menggunakan media digital yang membuatnya mengalami alienasi ganda (double alienation). Peserta didik terasing dari sesama di dekatnya (karena hanya dekat dengan orang jauh di dalam ‘handphone’) sekaligus terasing dari dirinya sendiri. Ketika kadar keterasingan semakin parah dan tantangan hidup menerpa dirinya sebagai remaja, sekaligus motivasi dan daya juang untuk bertahan rendah, peserta didik umumnya sulit keluar dari masalah, bahkan memilih jalan pintas. Kejadian bunuh diri berantai yang dilakukan beberapa remaja di Nusa Tenggara Timur (Ende, Kupang, Lewoleba) beberapa waktu lalu menjadi contoh nyata.
Apa yang Permanen?
Di tengah modernitas cair di mana peserta didik dipacu untuk berubah secara terus menerus dan cepat dalam dunia yang diliputi ketidakpastian dan tunggang-langgang ini, apa yang bisa diharapkan untuk permanen seperti batu karang di tepi pantai bagi peserta didik yang dituntut berubah?
Tentu bukan modernitas cair. Bukan pula Zygmunt Bauman. Bukan media digital dan robot atau Artifial Intelligence (AI), melainkan para pendidik di sekolah yang adalah manusia. Mengapa? Sebab robot atau AI tidak mempunyai hati dan perasaan. Hanya manusia yang dilengkapi iman, harapan dan cinta, mampu mendampingi peserta didik dengan pelbagai tantangan sekaligus dituntut untuk terus berubah di tengah dunia modern, yang juga selalu cair dan mengalir.
———————————–
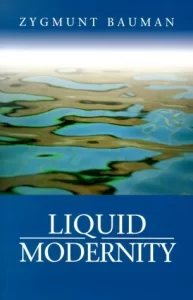








Tulisan teman sungguh luar biasa. Pertanyaan adalah: “Siapa atau apa yang salah.” Apakah yang salah adalah guru, murid, orang tua, sistem, atau perkembangan teknologi?” Bagi saya kita tidak sedang mempersalahkan siapa atau apa. Tetapi sesungguhnya lembaga pendidikan yang pertama dan utama adalah Keluarga
( Gravisimum Educationis srt. 3 ). Nilai-nilai hidup mestinya ditanam dan diperbiasakan kepada anak sejak dari keluarga. Sehingga anak terjun ke medan pendidikan baik pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi tidak terbawa arus modernisasi. Fondasi nilai dan moral telah terpatok membudaya dan menjadi milik pribadi yang diterima sejak dari keluarga. Ia tahu membedakan antara baik dan buruk, benar dan salah, boleh dan tidak boleh. Maka di jenjang pendidikan formal disiplin janganlah lentur, aturan dan tata tertib tidak sebatas tulisan penghias dinding ruangan.
Karena itu sebagai guru jaman ini kita tetap bangga dan bersemangat dalam melaksanakan tugas dengan setia dan bertanggung jawab. Kita bukan kaya harta tetapi kaya manusia dan tetap menjadi pahlawan tanpa tanda jasa.