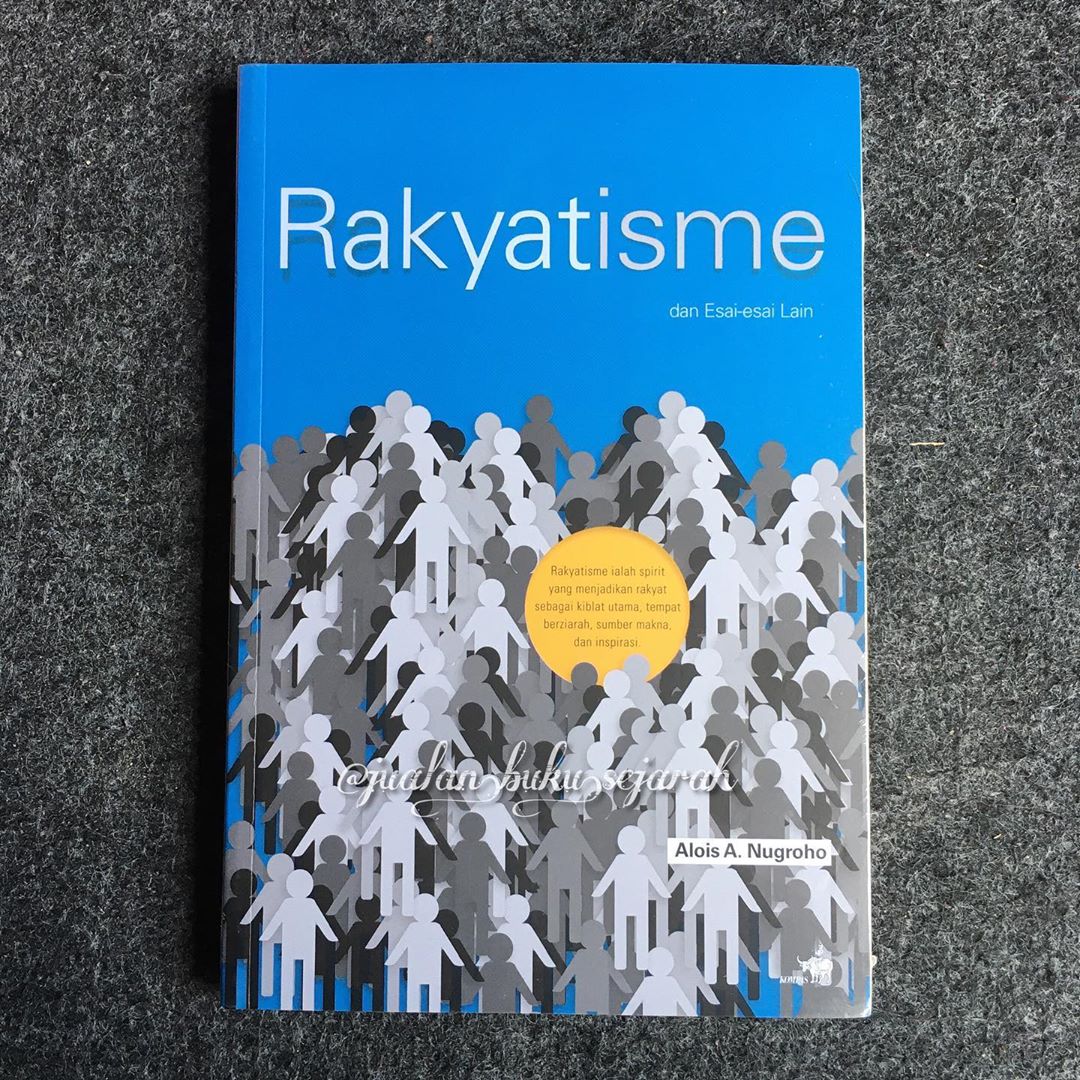Oleh Alois A. Nugroho
APA komentar Peter Drucker seandainya ia masih bisa membaca bahwa, dalam penilaian para pemuka lintas agama, birokrasi negara kita sangat rapuh sebagai akibat dari mudahnya para penegak hukum dipengaruhi uang? (Kompas, 21 Januari 2011). Salah satu kemungkinan Peter Drucker yang dijuluki “bapak manajemen modern itu” akan berpaling pada “bapak filsafat eksistianlisme”, Soren Kierkegaard (Drucker, 2010: 47-61).

Keabadian sebagai Alteritas
Kierkegaard menjadi relevan karena menyadarkan kita tentang adanya ketegangan dalam eksistensi manusia. Ketegangan itu terjadi antara eksistensi manusia dalam waktu dan eksistensi manuasia di luar waktu. Kita menyebut eksistensi manusia dalam waktu itu sebagai “hidup” dan menyebut eksistensi manusia di luar waktu sebagai “ada” (being). Dalam dimensi “hidup” horison imajinasi manusia adalah “mati”. Dalam dimensi “ada”, horison imajinasi manusia adalah “keabadian”.
Dalam ilmu administrasi, kita sudah belajar dari Stephen Covey bagaimana “kematian” menjadi horison imajinasi bagi birokrat dan manajer yang “proaktif” dan dengan demikian “efektif”. Di sini berlaku pula dalil Heidegger, bahwa orang yang otentik ialah yang memiliki anticipatory resoluteness terhadap kematian karena manusia adalah Sein-zum-Tode (Ada–ke-arah-kematian).
Orang proaktif, begitulah Covey, ialah orang yang peduli pada apa yang dipikirkan para pelayat tentang dirinya tatkala dia sudah terbujur sebagai jenasah. Bagi Covey, orang “efektif” ialah orang yang peduli pada “kenangan” yang akan tetap tumbuh dalam hati dan pikiran banyak orang ketika dirinya sudah tidak hidup lagi.
Dalam dimensi keabadian, kenangan orang-orang lain waktu kita mati bukanlah masalah utama. Masalah utama adalah bagaimana dalam hidup ini eksistensi sebagai “keabadian” dapat diaktualkan. Bagaimana dapat diwujudkan dalam perilaku konkret hidup sehari-hari di dunia sekarang, bahwa eksistensi kita punya dimensi “eternitas”. Dalam bahasa para agamawan, itu kurang lebih berbunyi bahwa eksistensi kita “tidak berasal dari dunia ini”.

Bagi Kiergegaard, dua dimensi itu berada dalam ketegangan. Eksistensi dalam waktu mendorong manusia untuk berkembang biak, agar spesies bertahan dan tumbuh kuat, untuk menafkahi hidupnya dan anak cucunya, untuk meraih kekuasaan, kemuliaan, kejayaan. Eksistensi dalam keabadian mendorong manusia untuk bergerak ke arah yang sebaliknya. Mengendalikan nafsu, sabar, berani mengalah, bela rasa, selalu siap mengampuni, adalah beberapa sikap yang dipupuk oleh eksistensi diri sebagai keabadian.
Penghayatan eternitas oleh eksistensi yang juga fana ini tidak jarang menimbulkan kecemasan (fear and trembeling). Bayangkan Anda bangun tidur dan tiba-tiba tersadar bahwa suatu saat Anda akan mati, tetapi akan tetap “ada” dan tidak dapat men-delete “ada’ Anda.
Perwujudan eksistensi eternitas dalam dunia temporal sering menimbulkan tragedi, bhkan juga di kalangan para pemuka agama. Secara tragis, agama dapat “jatuh” dan berubah menjadi usaha pribadi atau usaha bersama untuk mengakumulasi kekayaan, kekuasaan, kemuliaan, kejayaan duniawi. Buku harian Soren Kierkegaard sendiri, memuat banyak kritik atas praktik “organisasi dan administrasi” agama yang tragis.
Mengingat jauhnya perbedaan antara dua dimensi itu, bersama Hannah Arendt bisa kita katakan bahwa dimensi keabadian ialah “alteritas” dari dimensi keberwaktuan. Kita sering “banal”, “pragmatis” atau “mencari mudahnya saja”, dengan menutup mata dan telinga terhadap “alteritas”. Eksistensi kita sebagai keabadian tidak diajak berunding. Kita menganggap eksistensi keberwaktuan sebagai eksistensi keabadian.
Suara Hati Birokrat
Dalam konteks pemikiran Hannah Arendt, birokrat dan penegak hukum yang tidak “banal” ialah birokrat dan penegak hukum yang peduli terhadap “alteritas” berupa eksistensi sebagai keabadian. Mereka mendengarkan suara keabadian, suara “yang lain” dalam diri, yang dalam bahasa sehari-hari disebut “suara hati” atau “hati nurani”.

Dimensi keabadian perlu dipedulikan dalam perilaku profesional maupun perilaku sehari-hari, tidak hanya pada saat beribadah. Jangan sampai dalam perilaku profesional, para birokrat dan penegak hukum semata-mata bertindak atas “dorongan untuk hidup”, “mempertahankan kekuasaan”, atau “mencari kekayaan, kemuliaan dan kejayaan” yang lebih tinggi. Jangan sampai kita hanya bertindak berdasarkan “kebiasaan” begitu saja, tanpa memeriksa adakah yang kurang pas, kurang sreg, dilihat dari sudut keabadian. Jangan sampai kita bertindak hanya berdasarkan “semangat korps” atau “prosedur” semata, tanpa memperhatikan “suara hati” atau “suara keabadian”.
Bahkan dengan mengingat imbauan Stephen Covey saja, birokrat dan penegak hukum kita semestinya berusaha peduli pada bagaimana kelak hidupnya akan dikenang orang pada saat sudah meninggal, tak hanya pada bagaimana bergelimang kekayaan dan kejayaan semasa hidup. Sikap proaktif ini merupakan salah satu ciri dari birokrat yang “efektif”, yang akan menyebabkan birokrasi kita tidak serapuh sebagaimana dikeluhkan para pemuka lintas agama.
Namun, bagi Drucker, Kierkegaard, Arendt, “efektivitas sosial” bukanlah ukuran yang memadai. Dengan efektivitas sosial, birokrat kita akan sekadar menyesuaikan diri dengan kebiasaan-kebiasaan yang ada, atau dengan “semangat korps” semata-mata. Kita bisa saja dikenang sebagai “warga korps” yang “loyal”, bila tidak membuka korupsi yang dilakukan secara beramai-ramai. Kita akan berusaha untuk dikenang sebagai “bukan raja tega” oleh sanak kerabat yang menengadahkan tangan dan tak mau tahu darimana asal uang bantuan itu. Akibatnya, akan muncul keluhan bahwa birokrat dan penegak hukum kita rapuh, mudah tergiur oleh uang.
Dalam konteks ini, “mengambil nafas satu menit” untuk berkonsultasi dengan “suara keabadian” dalam diri menjadi sangat penting bagi para birokrat dan penegak hukum. Masalahnya, suara keabadian itu mungkin hanya berbisik lirih, sementara suara keberwaktuan dengan suara keras mendominasi ruang batin para birokrat, penegak hukum dan juga politisi. Kita berharap para birokrat, penegak hukum dan politisi masih mendengar desir keabadian yang lirih itu.
**************
Sumber Tulisan,Alois A. Nugroho, 2017, Rakyatisme dan Esai-esai Lain, Jakarta, Penerbit Buku Kompas.